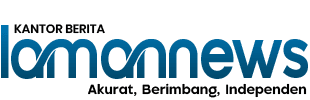Editorial
Situasi nasional saat ini sedang bergejolak. Sejumlah kota besar di Indonesia dilanda aksi unjuk rasa yang berujung rusuh, bahkan isu demo besar-besaran sudah ditetapkan waktunya, 1–5 September 2025. Ketidakpuasan publik terhadap pemerintah pusat mencuat, menambah daftar panjang kegagalan negara dalam menjawab keresahan rakyat.
Namun, Aceh menampilkan wajah berbeda. Di tanah Rencong, aksi mahasiswa dan rakyat 2 hari lalu justru berlangsung tertib, tanpa ada adegan bakar-bakaran atau kekerasan. Ada yang melihatnya sebagai kontras, ada pula yang membacanya sebagai strategi.
Aceh Bukan Pendatang Baru dalam Jeritan Ketidakadilan
Aceh sudah terlalu lama bersuara lantang soal ketidakadilan. Dari masa konflik bersenjata, perundingan Helsinki, hingga janji-janji otonomi khusus yang tak kunjung paripurna. Maka ketika daerah lain baru “meledak,” Aceh justru tampil tenang. Bukan berarti apatis, tetapi karena rakyat Aceh sudah lebih dulu kenyang dengan pahitnya politik Jakarta.
Momentum atau Keterpurukan?
Di titik ini, Aceh punya dua pilihan:
1. Menjadi Pemain
Aceh bisa memanfaatkan kerusuhan nasional sebagai momentum untuk kembali mengangkat agenda-agenda strategis: penuntasan butir-butir MoU Helsinki, masa depan dana otonomi khusus, serta distribusi keadilan fiskal dan politik. Dengan posisi pusat yang sedang rapuh, Aceh punya ruang untuk melakukan political bargaining.
2. Menjadi Penonton
Namun, jika elit politik Aceh hanya sibuk berebut kursi pilkada, jabatan di DPRA, dan proyek ekonomi rente, maka Aceh akan terpuruk. Suara rakyat akan kembali tenggelam, dan Aceh hanya jadi catatan kaki di tengah badai nasional.
Kemerdekaan Aceh – Retorika atau Realitas?
Isu kemerdekaan Aceh pasti selalu muncul setiap kali Jakarta goyah. Tetapi harus realistis, dukungan internasional minim, rakyat lebih sibuk dengan harga sembako dan listrik, sementara elite lokal tak punya konsensus. Maka, seruan merdeka hari ini lebih tepat dibaca sebagai alat tekan politik, bukan strategi nyata.
Aceh Harus Pilih Jalannya
Aceh saat ini sedang menunggu momen. Apakah memilih tampil sebagai wilayah “demo elegan” untuk menunjukkan kedewasaan politik, atau hanya menjadi penonton dalam kerusuhan nasional? Semua bergantung pada elite lokal, apakah mereka masih punya visi perjuangan, atau hanya sibuk bagi-bagi jatah.
Jika Aceh ingin dihormati, ia harus mengambil peran sebagai pemain politik strategis. Jika tidak, maka Aceh akan kembali terperosok dalam lingkaran apatisme, ditinggalkan sejarah, dan hanya dikenang sebagai tanah yang pandai berteriak tapi gagal bertindak.
Editorial ini menegaskan, Aceh punya agenda besar di balik kerusuhan nasional. Pertanyaannya tinggal satu, berani menjadi pemain, atau puas jadi penonton? (MS)