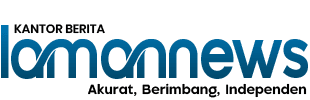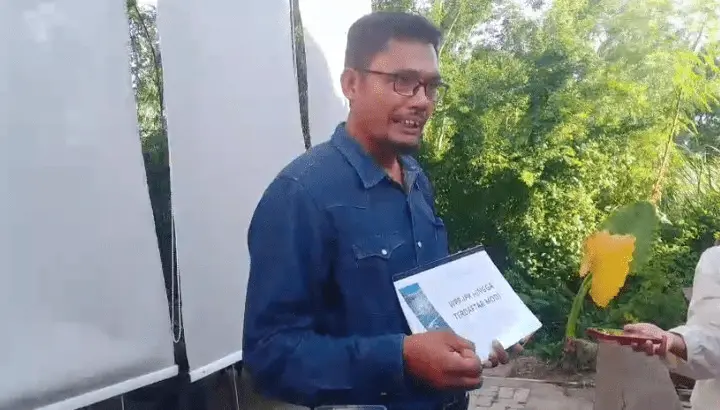Banda Aceh — Diskusi publik bertajuk “Mengurai Benang Kusut Tambang Ilegal, Uang Hitam, dan Solusinya” yang diselenggarakan Aceh Bergerak, Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) dan Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) pada Selasa, 7 Oktober 2025, menyorot akar masalah tambang rakyat dan kegagalan regulasi yang memicu konflik, praktik ilegal, serta kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah Aceh.
Acara yang di pandu oleh M. Nur dari FORBINA, dimulai pukul 13.30 WIB menghadirkan berbagai pemangku kepentingan; dari aktivis lingkungan, akademisi, perwakilan pemerintah hingga pelaku tambang. Salah seorang peserta, Muhammad Nasir (akrab disapa Abu Cik Ninja) — yang mengaku sebagai pelaku tambang sejak 1997 — menyampaikan pengakuan panjang dan kritik tajam terhadap kebijakan perizinan serta praktik di lapangan.
“Kami sudah mengurus izin — tapi pemerintah tak beri legalitas”
Nasir menjelaskan bagaimana masyarakat lokal berulang kali mengajukan legalisasi tambang rakyat, namun penetapan izin lebih banyak berpihak pada perusahaan besar. Ia menuturkan kronologi upayanya sejak 1997 hingga pengajuan ulang pada 2014–2015, termasuk pembuatan peta dan pengusulan kawasan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Namun, kata Nasir, berulang kali permohonan ditolak atau tak ditindaklanjuti karena alasan administratif, sehingga menimbulkan konflik antara warga dan aparat.
“Kami bukan pengamat, kami pelaku. Semua persyaratan yang diminta pemerintah sudah kami serahkan — tapi izin tidak keluar. Kalau ilegal, buktikan. Jangan terus salahkan masyarakat,” ujar Nasir di hadapan peserta.
Ia juga menantang pihak yang menuduh penambang tidak melakukan reklamasi untuk membuktikannya, sembari menegaskan bahwa komunitas adatnya memiliki aturan ketat soal tatacara usaha tambang dan pemulihan lahan.
Isu kunci yang muncul
Diskusi memetakan sejumlah masalah utama yang berulang di berbagai daerah tambang Aceh:
- Ketiadaan atau lambannya penerbitan izin WPR: Masyarakat mengaku telah mengajukan peta dan permohonan, namun belum memperoleh legalitas sehingga rentan dikatakan ‘ilegal’.
- Persekongkolan dan dugaan aliran uang gelap: Terdapat tudingan adanya setoran—yang menurut Nasir perlu dibuktikan—yang seolah memberi “perlindungan” terhadap operasi tambang ilegal.
- Ketidakjelasan tata kelola lahan: Banyak kawasan yang awalnya merupakan tanah ulayat atau adat telah dikuasai perusahaan, sementara akses masyarakat terpinggirkan.
- Dampak lingkungan dan tuntutan reklamasi: Kritik juga diarahkan kepada perusahaan besar; namun masyarakat mempertanyakan mengapa pihak yang menuduh tambang rakyat tidak menunjukkan contoh reklamasi perusahaan yang ideal.
- Perlunya sinkronisasi data dan peta: Ketiadaan peta cadangan yang jelas dipandang sebagai “kambing hitam” administrasi untuk menolak permohonan masyarakat.
Dorongan solusi: legalisasi, transparansi, dan penguatan tata kelola
Berdasarkan jalannya diskusi, beberapa rekomendasi praktis mengemuka:
- Percepatan penerbitan WPR dan izin tambang rakyat bagi komunitas yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
- Transparansi peta dan data tambang — agar proses perizinan tidak jadi ruang abu-abu yang memicu konflik.
- Penelusuran aliran dana jika ada indikasi “setoran gelap”, dengan mekanisme pengawasan dan audit independen.
- Standar reklamasi yang tegas diberlakukan untuk semua pelaku tambang (perusahaan maupun tambang rakyat) dan pengawasan implementasinya.
- Penguatan ekonomi lokal melalui akses legal ke pasar, pembinaan teknis, dan skema kemitraan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kami tak mau jadi penonton di negeri sendiri”
Nasir menutup sambutannya dengan pesan kuat: masyarakat tambang menuntut keadilan administratif dan peluang legal untuk mengelola sumber daya demi kesejahteraan lokal. Menurutnya, jika negara dan daerah tidak memberi akses legal, munculnya praktik ilegal dan konflik adalah konsekuensi yang dapat diprediksi.
Diskusi publik ini menegaskan kebutuhan kolaborasi lintas-pemangku kepentingan — pemerintah daerah, penegak hukum, akademisi, serta masyarakat adat — untuk menata ulang kebijakan pertambangan, menutup celah korupsi, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang adil serta berkelanjutan di Aceh.